Ramadan hampir usai. Kedai-kedai pangkas rambut penuh antre, bahkan sampai menjelang sahur. Setiap ingin tampil lebih fresh dan klimis di hari raya nanti, bersiap menyambut hari sukacita setelah sebulan puasa, seakan-akan sudah pasti mendapat rida dan rahmat dari Sang Segala Maha.

Jokowi pangkas rambut di Bogor, foto dari tribunnews.com
Syahdan, ada suatu kisah tentang seseorang yang menunaikan ibadah haji tertidur lelap ketika wukuf di tengah teriknya matahari di padang Arafah. Dalam tidurnya ia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah saw.
Perasaan berjumpa dengan Rasulullah ini memberikan harapan dalam dirinya bahwa hajinya telah menjadi haji mabrur. Namun untuk kepastian, ia memberanikan diri bertanya, “siapakah di antara mereka yang diterima hajinya sebagai haji mabrur, wahai Rasulullah?”
Rasulullah, seraya menarik napas dalam-dalam menjawab, “tak seorangpun dari mereka yang diterima hajinya, kecuali seorang tukang cukur tetanggamu.”
Serta-merta sang haji tersebut terkejut, kaget tapi kagum. Bagaimana tidak, ia tahu persis bahwa tetangganya itu miskin, dan terlebih lagi bahwa tahun ini ia tidak menunaikan ibadah haji.
Dengan digeluti perasaan sedih, dadanya serasa sesak, ia terbangun dari tidurnya. Sepanjang melakukan wukuf, sang haji tersebut introspeksi diri, memikirkan dalam-dalam apa arti di balik mimpi tersebut.
Sekembali dari Mekah, ia segera menemui tetangganya, Si Tukang Cukur. Ia dengan bangga menceritakan segala pengalamannya selama menunaikan ibadah haji. Tapi cerita yang paling ingin disampaikan adalah perihal mimpinya tentang si tukang cukur itu. Dengan sikap keheranan, ia pun bertanya, “amalan apakah yang anda lakukan sehingga anda dianggap telah melakukan haji mabrur?”
Tetangganya pun heran. Namun dengan tenang bercampur haru ia bercerita, bahwa sebenarnya, ia telah lama bercita-cita untuk dapat menunaikan ibadah haji. Dan telah bertahun-tahun pula ia mengumpulkan biaya. Namun ketika biaya telah cukup, dan tibalah pula masa untuk berhaji, tiba-tiba seorang anak yatim tetangganya ditimpa musibah yang hampir merenggut jiwanya. Maka Si Tukang Cukur menyumbangkan hampir keseluruhan biaya yang telah bertahun-tahun dikumpulkan itu untuk membiayai anak yatim tersebut, sehingga ia gagal menunaikan ibadah haji.
Bermulanya Ramadan, saling hujat dan caci menghiasi jejaring sosial. Kelompok yang satu menuding kelompok lainnya sesat, kelompok lain menuduh yang satunya telah melecehkan. Kelompok satu bilang yang dua salah dan kelompok dua kukuh punyanya yang benar, kecuali itu salah. Intinya adalah masing-masing meyakini gerombolannyalah yang pasti masuk surga, yang lainnya tidak.
Fenomena ini terus berulang, menjadi siklus tahunan. Seharusnya kita sadar, bahwa ternyata kita kadang keliru dalam upaya mencari rida Allah. Rida-Nya terkadang diburu dengan semangat egoisme yang berlebihan dan tanpa disadari justru bertolak belakang dengan keridaan-Nya. Dengan kata lain, betapa ibadah-ibadah kita sering ternoda oleh lumpur kepicikan egoisme pelakunya, jauh dari nilai-nilai “kasih sayang” (rahmatan lil ’alamin).
Egoisme, berasal dari kata ego, yang berarti diri pribadi. Dalam oxforddictionaries.com, definisi singkat ego adalah "A person's sense of self-esteem or self-importance."
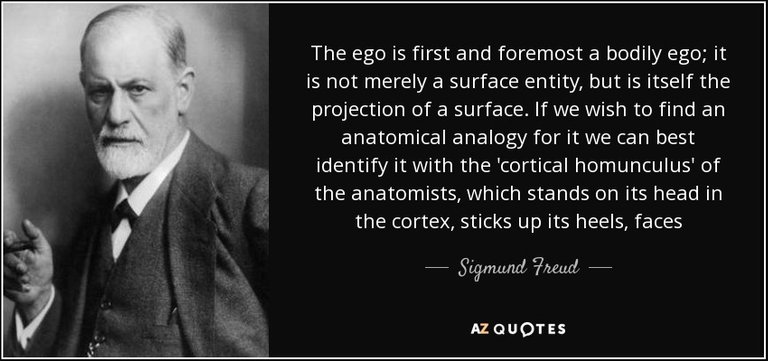
Sigmund Freud tentang ego, dari laman azquotes.com
Egois adalah sifat bawaan setiap manusia, dan itu tidak bisa dipungkiri. Hanya saja kadar egois setiap diri manusia berbeda-beda. Setiap orang berhak untuk lebih mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain. Allah sendiri sudah berfirman, “quu anfusakum” terlebih dulu. Tapi, bukan berarti kita harus menganggap nihil orang lain. Toh, kita ada, juga karena orang lain. Kita bisa lebih justru karena orang lain sedang kekurangan.
Jadi, akan egois, kalau kita terlalu memaksakan bahwa apa yang kita yakini adalah benar-benar benar. Mengapa kita tidak mencoba belajar, walaupun kita benar, orang lain belum tentu salah? Lagipun, empat, bukan hanya hasil dua ditambah dua saja.
Dan, akan sangat egois, tentu saja, bila kita tidak pernah mau mengakui kalau kita ini salah. Kita adalah bejat. Kita hanya mau menunjukkan “inilah saya”, kalau itu benar. Tapi ketika berbuat dosa, kita selalu berdalih dengan iblis.
Kalau memang biang kerok semua kesalahan kita adalah iblis, kenapa di bulan yang agung ini kita masih secara sadar berlaku seperti prilaku iblis? Padahal, kata para teungku di kampung dan ustaz-ustaz di kota, di bulan Ramadan, para iblis beserta kaki tangannya dalam kondisi terbelenggu.
Kalau begitu, siapa yang lebih egois? Iblis, atau kita--yang hanya bisa mengkambinghitamkan iblis?*
*dari arsip catatan lama; 2005, diperbarui agar kekini-kinian